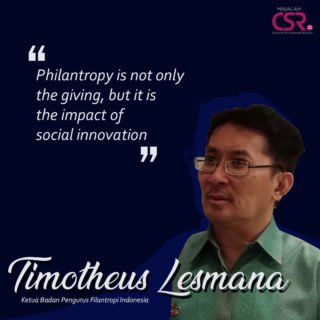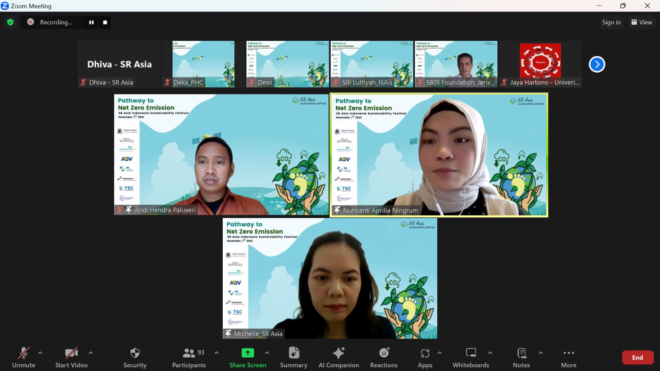Jakarta, MajalahCSR.id – Isu pekerja anak yang menerpa berbagai sektor industri di Indonesia bukanlah masalah baru. Isu ini seringkali jadi bola liar yang mempengaruhi citra industri itu sendiri secara negatif. Jumlah pekerja anak ini makin bertambah, terlebih saat pandemi seperti sekarang ini, di mana roda ekonomi yang belum sepenuhnya pulih mendorong anak-anak dari keluarga rentan tereksploitasi demi membantu perekonomian orang tuanya.
Menurut laporan Survey Angkatan Kerja Nasional seperti yang dikutip dari Liputan6.com, Rabu (15/6/2022) pada Agustus 2020, terdapat 3,36 juta anak Indonesia tercatat sebagai pekerja, dan 1,17 juta anak di antaranya adalah pekerja anak. Sementara risiko pertambahan jumlah pekerja anak ini, masih dari sumber yang sama, bisa mencapai 9 juta anak. Sementara menurut sumber dari Katadata, pekerja anak di usia 10 – 17 tahun pada periode 2021 adalah 2,63% dari total pekerja di Indonesia.
Meskipun ini merupakan isu global, namun bisa jadi alat ampuh untuk menyerang citra korporasi di Indonesia. Bahkan bagi sebagian oknum, hal ini dapat dijadikan tuduhan tak berdasar bagi perusahaan (yang benar-benar tak melakukan). Ketika melihat seorang anak beraktivitas di lahan perkebunan perusahaan, contohnya, padahal ia hanya bermain menunggu orang tua yang bekerja di sana, bisa jadi dijadikan framing seolah dia adalah pekerja anak oleh pihak tak bertanggung jawab. Lantas bagaimana mengelola isu ini dikaitkan dengan “stakeholder engagement” atau pelibatan pemangku kepentingan?
Menurut Dito Santoso, Senior Editor di MajalahCSR.id, menukil dari laporan World Economic Forum, kondisi pandemi yang mengubah wajah dunia sekarang ini berdampak pada beragam sektor. Dampak yang ditimbulkan umumnya cukup buruk, utamanya pada interaksi komunikasi antar manusia yang secara fisik terganggu atau kerekatan sosial yang meluntur (meskipun di sisi lain perkembangan teknologi digital terakselerasi), hingga pada krisis ketahanan ekonomi masyarakat.
Hal ini disampaikan Dito dalam webinar learning season “Membangun Kemitraan dan Perencanaan Program yang Efektif untuk Penanggulangan Pekerja Anak” yang diinisiasi oleh PAACLA (Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture), Kamis (8/9/2022), pekan kemarin.
Mengenai undang-undang terkait pekerja anak juga di Indonesia sudah ada ratifikasinya. “Di Indonesia sudah ada aturan yang berlaku, mulai dari pengesahan ILO Convention tentang ‘minimum age’ untuk bekerja,” kata Dito. Namun, demikian Dito mencoba menarik permasalahan ini ke lingkup yang lebih luas, yaitu hak asasi manusia. “Karena ketika kita menghormati hak anak, maka itu merupakan bagian dari (upaya) menghormati hak asasi manusia,” cetusnya.
Bahkan merujuk pada 10 prinsip UN Global Compact, terutama pada prinsip kelima, secara gamblang berbunyi “Business should uphold the abolition of child labour” dengan kata lain pasal ini berbunyi soal bagaimana bisnis itu bisa menghapuskan pekerja anak. Melalui prinsip ini juga permasalahan pekerja anak sudah menjadi bagian dari kepedulian dan kesepakatan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk bisa mensolusikannya secara baik dan benar.
Sementara itu di ISO 26000 yang membahas tentang Tanggung Jawab Sosial menyuarakan hal ini. “Dalam salah satu subyeknya menyebutkan bahwa wajib hukumnya bagi perusahaan untuk tidak merekrut atau mempekerjakan pekerja anak. Karena hal ini sudah menjadi mandatory (wajib dijalankan) dan merupakan bagian pernghormatan terhadap hak asasi manusia,” sebut Dito.
Respon korporasi
Lalu bagaimana bisnis meresponnya? “Saya kira kita perlu melihat bagaimana bisnis itu memandang sebuah isu. Bagaimana sebuah isu itu bergerak menuju sebuah risiko,” cetusnya. Meskipun demikian, itu tidak sekedar hanya ada di sektor bisnis saja. Di sektor sipil (civil society/organisasi masyarakat sipil), misalnya, bagaimana mereka menangani sebuah isu, apakah itu bisa menjadi masalah dan menimbulkan dampak yang lebih besar ketika tidak dikelola secara intensif saat ini.
Isu-isu yang seperti itu, DIto mengingatkan, akan terus bergulir seperti bola salju sehingga akan terus membesar. Biasanya jika seperti ini, perusahaan akan melihatnya dalam tataran yang praktis yaitu apakah isu itu akan berisiko pada perusahaan secara keseluruhan. Dalam konteks ini isu yang dimaksud adalah isu pekerja anak.
“Contoh praktik perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menggunakan ‘family system’, isu ini akan menjadi sangat sensitif dan sangat rentan dan berisiko,” katanya kembali mengingatkan. Isu ini menjadi perhatian dan mendorong asosiasi kelapa sawit global, RSPO (Roundtable Sustainability Palm Oil), untuk mengeluarkan peraturan perlindungan pekerja anak di perkebunan kelapa sawit. Ketika isu ini sudah dikelola menjadi “risk management” dan dikelola secara rutin, maka akan menjadi isu yang strategis, sehingga bisa menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan.
Isu pekerja anak sudah seharusnya menjadi isu strategis yang ditangani oleh berbagai sektor, mulai dari swasta dengan korporasinya, pemerintah, dan organisasi sipil. “Bagaimana cara menggerakannya ke arah sana sehingga antar sektor bisa memahami satu sama lain dan bekerja sama?”
Identifikasi isu material
Korporasi, jelas Dito, akan memandang hal ini sebagai isu sosial yaitu isu hak asasi manusia, lalu mengomunikasikannya ke pemangku kepentingan mereka melalui laporan keberlanjutan perusahaan (sustainability report). Hal pertama yang perlu dilakukan bagi sektor bisnis dan sektor lainnya adalah mengindentifikasi isu material. Ketika isu ini akan diangkat menjadi sesuatu yang strategis, maka harus memahami jenis industrinya atau sektor di mana isu itu berada. Lalu memahami profil perusahaan (jika yang dibahas adalah perusahaan), kemudian isu dan pemangku kepentingan. Ketika kita mengindentifikasi isu, maka isu (pekerja) anak itu tergaolong dalam kategori isu apa.
Kembali ke sektor perusahaan perkebunan sebagai contoh (karena isu pekerja anak lebih banyak terjadi di sektor ini, juga sektor pariwisata), aspek hak asasi manusia (dalam konteks human right intake assessment) yang harus diperhatikan karena akan dilihat dari konteks hak buruh, hak masyarakat adat, hak anak, hak perempuan, dan atas lingkungan. Ketika poin-poin tersebut sudah bisa dikaji maka akan menjadi bagian dari implementasi prinsip bisnis dan HAM perusahaan.
Prinsip itu terbagi menjadi kegiatan kebijakan publik (perusahaan terkait) HAM, penilaian dampak HAM, pelacakkan kinerja HAM, dan pengintegrasikan HAM. Hal-hal tersebut jika ditarik ke lingkup yang lebih luas bisa berarti akan berbicara soal “human right due diligence”.
“Ketika perusahaan perlu mengindentifikasi isu dan memperoleh landasan asesmen yang jelas, maka perlu melakukan ‘human right due diligence’. Penerapannya seperti ada isu apa yang terjadi di lapangan terkait pekerja anak, apakah bersinggungan dengan praktik bisnis dan rantai pasok perusahaan, apakah perusahaan sudah memiliki kebijakan publik untuk menanggulangi hal itu, serta bagaimana ragam mekanisme pendukungnya, seperti SOP, dan SDM yang tersedia.” Hal ini perlu dikaji di sepanjang rantai pasok.
Contoh di perkebunan, sebagai upaya mitigasi, perusahaan mendirikan tempat penitipan anak, ketika orang tuanya bekerja di kebun smallholder yang berafiliasi ke perusahaan. Hal ini sebagai upaya mencegah terjadi anggapan keliru pihak luar saat mendapati sang anak memunguti buah dari kebun yang disangka pekerja anak, padahal mereka kenyataannya sedang bermain di kebun.
“Langkah kedua adalah memetakan pemangku kepentingan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh isu (pekerja anak) tersebut,” Dito meneruskan. Jika isu tersebut berdampak besar bagi perusahaan dan pemangku kepentingan memiliki kepedulian atau kepentingan yang tinggi terhadap isu tersebut yang dalam hal ini adalah pekerja anak. Jika sudah diidentifikasi dan berada dalam posisi seperti itu maka isu ini sepatutnya menjadi prioritas perusahaan untuk memitigasinya.
Tidak cukup di sana perusahaan harus punya kebijakan tertinggi yaitu visi misi, lalu diturunkan ke mekanisme seperti ke sumber daya manusia dan praktik kerja. Dari sini perlu dilakukan pendekatan program, misalnya perusahaan melakukan kerja sama secara intens dengan pemangku kepentingan. Hal ini karena isu tersebut berdampak besar bagi korporasi dan pemangku kepentingan pun menaruh perhatian tinggi. Praktik kolaborasinya bisa berupa pemberdayaan, serta pelibatan pemangku kepentingan dalam program mitigasi.