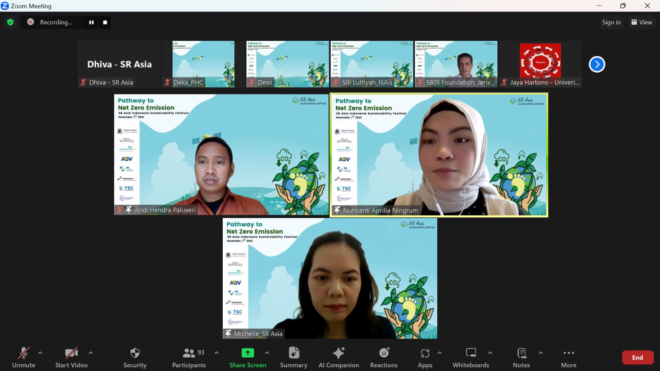MajalahCSR.id – Rasio elektrifikasi Indonesia terus meningkat dalam kepemimpinan Joko Widodo terbukti dengan angka rasio elektrifikasi yang berhasil meningkat dari angka 84,35%, ke angka 99,2% dalam kurun waktu 2014-2020. Walaupun terlihat berhasil menyediakan tenaga listrik kepada nyaris masyarakat Indonesia, namun pembangkit tenaga listrik yang disediakan mayoritas berasal tenaga uap (PLTU) berbahan batu bara yang menimbulkan kerusakan sosial dan lingkungan.
Bauran energi pembangkit listrik didominasi oleh batu bara sebesar 62,98% dan gas sebesar 21,4%. Sedangkan Energi Baru Terbarukan hanya menyumbang bauran energi sebesar 11,5% dan BBM sebesar 4,18%.
Sektor kelistrikan adalah salah satu sektor yang rentan terjadinya konflik kepentingan. Hal ini karena beberapa nama yang berposisi sebagai pejabat publik aktif atau terafilisasi dengan mereka yang menduduki jabatan tersebut politically-exposed persons (PEPs) turut memiliki bisnis PLTU. Keterkaitan antara bisnis dan politik di Indonesia masih sangat erat. Dengan hadirnya PEPs di perusahaan pengelola PLTU, baik BUMN maupun non-BUMN memberikan sinyal bahwa petinggi perusahaan, khususnya komisaris dan jajaran direksi diangkat karena memiliki akses ke pengambil kebijakan.
“Banyak kebijakan publik dibuat berdasarkan pertimbangan politik dan kepentingan ekonomi politik elit daripada kalkulasi teknis dan rasional,” ungkap Danang Widoyoko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) dalam keterangan tertulisnya.
Untuk menilai transparansi keterlibatan politik perusahaan di sektor kelistrikan Indonesia, Transparency International Indonesia (TII) melakukan kajian dan penilaian yang bertajuk “Corporate Political Engagement Index: Penilaian terhadap 90 Perusahaan Pengelola PLTU di Indonesia”. Sebanyak 90 perusahaan yang mensponsori, membangun, dan mengoperasikan PLTU di wilayah Indonesia menjadi objek penilaian laporan ini. Sumber data yang diteliti oleh TI-Indonesia adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan yang terbit dalam periode 2018-2020 dan dapat diakses secara bebas oleh publik.
“Dari 90 perusahaan pengelola PLTU di Indonesia yang dinilai oleh TI Indonesia, skor keseluruhan Corporate Political Engagement Index hanya 0.9/10. Hal ini tentu sangat buruk karena menandakan perusahaan yang berbisnis PLTU di Indonesia sangat tidak transparan terkait aktivitas politiknya. Tentu saja ini menjadi lahan rawan korupsi dan konflik kepentingan,” ungkap Bellicia Angelica, peneliti TI-Indonesia.
Dalam penilaian ini, Corporate Political Engagement Index mengacu pada penilaian lima dimensi, yaitu dimensi lingkungan pengendalian (rerata skor hanya sebesar 10%), dimensi donasi politik (rerata skor 15%), dimensi lobi yang bertanggung jawab (rerata skor 5%), dimensi praktik keluar masuk pintu/revolving door (rerata skor 1%), dan dimensi transparansi dalam pelaporan aktivitas politik perusahaan (rerata skor 13%).
Dalam melakukan analisis, TI Indonesia juga membandingkan perolehan nilai CPEI antara perusahaan yang dimiliki oleh negara (BUMN/BUMD), modal internasional, oligarki dan modal domestik serta perusahaan patungan. Ada beberapa temuan yang menjadi poin menarik dalam analisis TI Indonesia. Pertama, rerata skor CPEI perusahaan yang dimiliki oleh modal negara (rerata skor 2,18) lebih tinggi dibandingkan dengan skor CPEI perusahaan terkait dengan oligarki (1,16) dan modal internasional (0,18).
Akan tetapi, skor CPEI perusahaan patungan modal negara, baik kerja sama perusahaan negara dengan oligarki dan modal internasional lebih rendah dari perusahaan negara induknya dengan perolehan rerata skor 0,00 bagi dua kategori tersebut. Kedua, banyak perusahaan yang mendapatkan skor CPEI nol; dari 90 perusahaan, ada 59 perusahaan yang mendapatkan nilai nol.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa negara tidak mengatur secara ketat pengelolaan modal dan interaksi antara perusahaan dengan pejabat publik. Perusahaan juga bisa leluasa melakukan lobi, memberikan pendanaan dan berbagai interaksi lainnya dengan pengambil kebijakan, baik pejabat negara atau pemerintah atau politisi.
Selain membandingkan skor CPEI perusahaan, TI Indonesia juga berupaya untuk melihat Politically Exposed Persons (PEPs) di tiap perusahaan. Sederhananya, PEPs dapat didefinisikan sebagai orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik di dalam struktur perusahaan. Dalam mendefinisikan PEPs sendiri, TI Indonesia mengacu pada definisi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Financial Action Task Force (FATF). TI Indonesia menggolongkan PEPs ke dalam enam kategori latar belakang, yaitu birokrasi, orang dekat PEP, jabatan strategis, penegak hukum, militer, dan politisi.
Hasilnya, ada 132 PEPs yang tersebar di 40 dari 90 perusahaan. Adapun rincian dari 132 PEP tersebut adalah 47 berlatar belakang birokrasi, 32 orang dekat PEP, 37 orang dengan jabatan strategis, 4 orang penegak hukum, 9 orang dari latar belakang militer, dan 3 orang berlatar belakang politisi. Umumnya, PEP ini ditempatkan dalam jajaran komisaris.
Hadirnya PEPs dalam perusahaan pengelola PLTU disinyalir akan membuka lebar akses kepada pengambil kebijakan. Dalam perusahaan milik negara, PEP juga dapat berfungsi sebagai patron karena yang direkrut sebagai PEP adalah pendukung pemegang kekuasaan atau memiliki jasa besar dalam kompetisi politik.